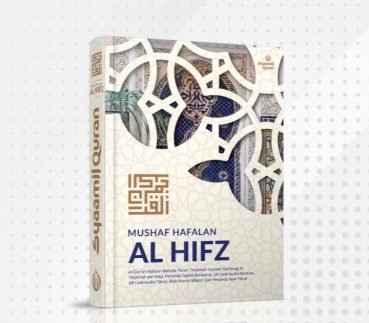WARTAIDAMAN.com
Penulis: Ndoro Kakung
Suatu sore yang biasa di sebuah kafe pinggiran kota, seorang lelaki paruh baya duduk di dekat jendela. Kopinya sudah dingin, senjanya sudah layu, tapi ia masih terpaku pada layar kecil di genggamannya. Matanya bukan lagi mencari kabar, melainkan sekadar menggulung ke bawah, lalu ke atas, ke bawah lagi, tanpa tujuan.
Ia bukan satu-satunya. Di sudut lain, sepasang kekasih duduk tanpa kata. Cinta mereka kini jadi algoritma, bukan tatap mata.
Fenomena ini begitu banal tapi mendalam: kita terus-menerus menunduk—bukan karena rendah hati, tapi karena layar lebih memesona dari dunia nyata. Kita membangun katedral digital dari detik-detik kosong yang seharusnya bisa diisi dengan percakapan, perenungan, atau sekadar keheningan.
Media sosial hari ini bukan sekadar tempat berbagi cerita. Ia sudah menjelma seperti mesin slot Las Vegas di saku celana—memompa harapan, mengatur emosi, dan menyemburkan dopamin dalam dosis kecil tapi intens.
“It’s not just a distraction, it’s a designed addiction,” ujar Tristan Harris, mantan desainer etika di Google dan pendiri Center for Humane Technology.
Dalam dokumenter “The Social Dilemma”, Harris menjelaskan bahwa media sosial bukan lagi alat, tapi makhluk hidup digital yang tahu cara menghisap perhatian dan memelihara kecemasan. Kita tak sekadar menggunakan medsos—kita dikunyah olehnya perlahan-lahan.
Psikolog media dari University of Michigan, Ethan Kross, dalam bukunya, “Chatter: The Voice in Our Head”, menyebut bahwa scrolling yang tak berkesudahan adalah cara manusia modern menenangkan kegelisahan batin, meskipun efeknya sering justru memperparah kecemasan. “Media sosial memberi ilusi koneksi, tapi sering membuat kita kesepian di tengah keramaian digital,” tulisnya.
Seperti seseorang yang tenggelam tapi malah memeluk batu, kita terus membuka aplikasi demi pelarian. Ironisnya, pelarian itu justru membelenggu kita lebih dalam.
Konten hari ini bukan hanya cermin, tapi juga kompas dan kabut. Algoritma memilihkan isi kepala kita, bahkan sebelum kita sadar ingin memikirkannya. Saat bangun tidur, jempol kita lebih dulu menyentuh layar sebelum menyentuh kehidupan.
Kita tak lagi hidup dalam waktu nyata, tapi dalam ekor panjang notifikasi. Bahkan diam kini terasa ganjil—seolah dunia sedang terjadi di tempat lain. Fear of Missing Out (FOMO) bukan sekadar istilah psikologi pop; ia adalah desakan yang nyata, tajam, dan kadang menyakitkan.
Apa yang bisa kita lakukan saat dunia terlalu ramai?
Lepas dari media sosial bukan berarti jadi pertapa digital. Tapi kita perlu rewiring, seperti yang dilakukan oleh pecandu gula saat mulai makan sehat. Detachment bukan pelarian, tapi penyembuhan. Kita perlu mengganti “scrolling” dengan “strolling”—melangkah perlahan di dunia nyata.
Mulailah dari sunyi. Latihan tidak mengunggah apa pun saat momen indah terjadi. Biarkan momen itu berdiam dalam ingatan, bukan algoritma.
Ada kehidupan yang bisa disentuh, yang bisa disenyumi tanpa emotikon, yang bisa didengar tanpa speaker. Ada hening yang tidak membosankan, dan ada cinta yang tidak perlu dibuktikan lewat story 15 detik.
Media sosial bukan musuh. Tapi ia bukan tuan rumah yang netral. Jika kita tak sadar sedang duduk di meja perjudiannya, bisa jadi kita adalah taruhannya.
Maka, pertanyaannya bukan “kenapa kita kecanduan?”, tapi: apa yang bersedia kita korbankan agar tidak kehilangan diri sendiri?
*hadi/ pjmi uia/ wi/ nf/ 020525
Views: 25